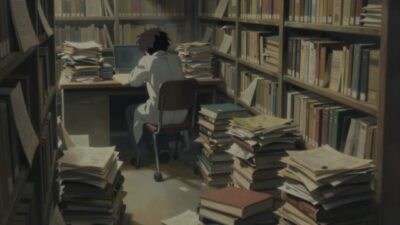DUA PULUH tahun bukan waktu yang singkat bagi sebuah masyarakat yang pernah hidup dalam konflik. Namun di Aceh, rasa damai yang hadir setelah penandatanganan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 kerap terasa belum utuh. Sesekali, suara miring dari sebagian elite politik di pusat muncul, bahkan ada yang menyindir rakyat Aceh “sedikit-sedikit bicara Helsinki”.
Sindiran itu tentu menggugah tanya. Mengapa masyarakat Aceh masih merujuk pada perjanjian damai yang usianya sudah dua dekade? Apakah MoU Helsinki benar-benar sudah tuntas, atau justru masih menyimpan pekerjaan besar yang belum terselesaikan?
Untuk memahami sensitivitas ini, kita perlu masuk ke akar persoalan. MoU Helsinki bukan sekadar dokumen politik. Ia adalah titik balik yang menghentikan konflik bersenjata selama hampir 30 tahun, konflik yang merenggut puluhan ribu nyawa, memecah keluarga, dan meluluhlantakkan ekonomi lokal.
Baca juga: Refleksi 20 Tahun MoU Helsinki, Pengamat Aceh: Perdamaian Jangan Malah Melemahkan!
Dan, seperti banyak perjanjian damai di berbagai belahan dunia, MoU Helsinki memuat kesepakatan yang rumit; tentang politik, ekonomi, keamanan, dan identitas. Total ada 45 butir kesepakatan, mulai dari pembentukan partai lokal, reintegrasi mantan kombatan, hingga pengaturan sumber daya alam.
Tetapi di sinilah masalah muncul. Tidak semua butir itu berjalan mulus.
Kesenjangan yang Melebar
Pada 2021, Pemerintah Aceh membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan MoU Helsinki. Temuan mereka cukup tegas. Banyak aspek MoU belum terealisasi sepenuhnya. Kunci persoalannya adalah kurangnya aturan turunan dari UUPA (UU No. 11 Tahun 2006); undang-undang yang seharusnya menjadi jembatan dari meja perundingan ke kebijakan nyata.
Kajian akademik dari berbagai universitas di Indonesia mengidentifikasi beberapa masalah utama:
1. Kewenangan Politik yang Setengah Hati
MoU memberikan ruang bagi Aceh untuk membentuk partai politik lokal dan mengatur sistem politik daerah secara lebih otonom. Namun dalam praktiknya, penafsiran pusat dan daerah sering bertabrakan. Partai lokal memang hadir, tetapi kewenangan politik yang lebih besar tidak sepenuhnya diberi ruang.
Baca juga: Realisasi APBA 2025: Ilusi atau Pertaruhan Kompetensi?
2. Lambang, Bendera, dan Identitas
Aceh memiliki hak simbolik untuk menetapkan lambang dan bendera daerah. Namun kebijakan ini menghadapi hambatan hukum dan politik yang panjang. Kajian hukum menunjukkan bahwa implementasinya memerlukan itikad baik dari pemerintah pusat; sesuatu yang hingga kini masih diperdebatkan.
3. Reintegrasi Mantan Kombatan dan Korban Konflik
MoU mengamanatkan reintegrasi ekonomi dan sosial, tetapi banyak kebijakan tidak berumur panjang. Program bantuan tidak selalu berkelanjutan, dan badan yang bertugas menjalankan reintegrasi sering kehilangan dukungan regulasi dan anggaran.
Baca juga: Saat Membahas Revisi UUPA, JK: Otsus Aceh Perlu Diperpanjang
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam
Aceh seharusnya memiliki kewenangan lebih luas dalam pengelolaan minyak, gas, dan sumber daya laut. Namun hubungan pusat–daerah pada sektor ini masih sering dipenuhi ketegangan, baik terkait bagi hasil maupun otoritas izin eksplorasi.
Ketika ada anggota DPR RI yang merasa “gerah” jika masyarakat Aceh bicara soal MoU Helsinki, ada jarak pemahaman yang tercermin di sana. Bagi rakyat Aceh, MoU bukan sekadar wacana politik melainkan jaminan moral dan janji negara bahwa masa konflik tidak akan kembali.
Maka, wajar jika komentar semacam itu memicu reaksi keras. Ia seperti meminta sebuah masyarakat melupakan resep penyembuhan, sementara luka mereka belum sembuh sepenuhnya.
Damai tidak Sekadar tidak Ada Tembakan
Di bidang ilmu perdamaian, dikenal istilah “positive peace”—damai yang bukan sekadar tiadanya kekerasan, melainkan hadirnya keadilan, partisipasi, serta pembangunan yang layak.
Banyak penelitian menyimpulkan bahwa Aceh saat ini berada di posisi “damai negatif”. Tidak ada perang, tetapi ketidakadilan struktural masih terasa.
Tidak heran jika sebagian masyarakat Aceh masih merasa MoU Helsinki seperti dokumen yang dipajang, bukan pedoman yang dijalankan.
Pernyataan bernada meremehkan dari elite politik bukan hanya soal pilihan kata; ia berpotensi mengikis kepercayaan publik Aceh terhadap komitmen negara. Jika itu dibiarkan, risikonya bukan hanya ketegangan politik, tetapi juga:
- penurunan kepercayaan pada institusi pemerintah,
- munculnya kelompok-kelompok protes baru,
- meningkatnya alienasi generasi muda Aceh dari pemerintah pusat, serta
- potensi menghidupkan kembali sentimen-sentimen lama yang seharusnya sudah diredam oleh MoU.
Dalam studi perdamaian, kondisi semacam ini disebut “post-conflict stress fracture”—retakan-retakan halus yang jika dibiarkan bisa membesar.
Apa yang Seharusnya Dilakukan?
Para akademisi, pemerhati perdamaian, hingga lembaga internasional sama-sama menyampaikan hal yang relatif serupa:
1. Percepat Regulasi Turunan UUPA: Tanpa aturan teknis, MoU akan terus macet dalam birokrasi.
2. Bangun Dialog yang Jujur Pusat–Aceh: Bukan dialog seremonial, tetapi komunikasi yang menyentuh persoalan mendasar.
3. Perkuat Kelembagaan Reintegrasi: Program untuk mantan kombatan dan korban konflik harus berkelanjutan, bukan sporadis.
4. Edukasi Publik Nasional: Sebagian besar masyarakat di luar Aceh tidak memahami isi MoU Helsinki. Edukasi seputar sejarah konflik dan perjanjian damai dapat mengurangi stigma dan salah kaprah.
Damai adalah Proyek Panjang, bukan Acara Seremonial
MoU Helsinki bukan dokumen sakral yang tak boleh digugat; ia dapat dikritik, dikaji ulang, dan dibenahi. Tetapi meremehkannya tanpa memahami luka sejarah justru berisiko membuka kembali pintu-pintu ketidakpercayaan.
Aceh tidak meminta keistimewaan berlebihan. Yang diminta hanya satu: jalankan apa yang telah disepakati bersama.
Karena bagi rakyat Aceh, Helsinki bukan sekadar lembaran kertas. Ia adalah jembatan menuju kehidupan yang lebih adil. Dan, selama jembatan itu belum kokoh, menyebutnya bukanlah “sedikit-sedikit”.
Itu adalah cara masyarakat menjaga warisan damai yang mereka bangun dengan darah dan air mata. Saat sering diingatkan saja tentang Mou Helsinki di berbagai kesempatan, para elit tidak menganggapnya ada. Apalagi kalau sudah terkubur sejarah.[]
Dr. Taufik Abd. Rahim; adalah pengamat kebijakan publik dan akademisi Aceh