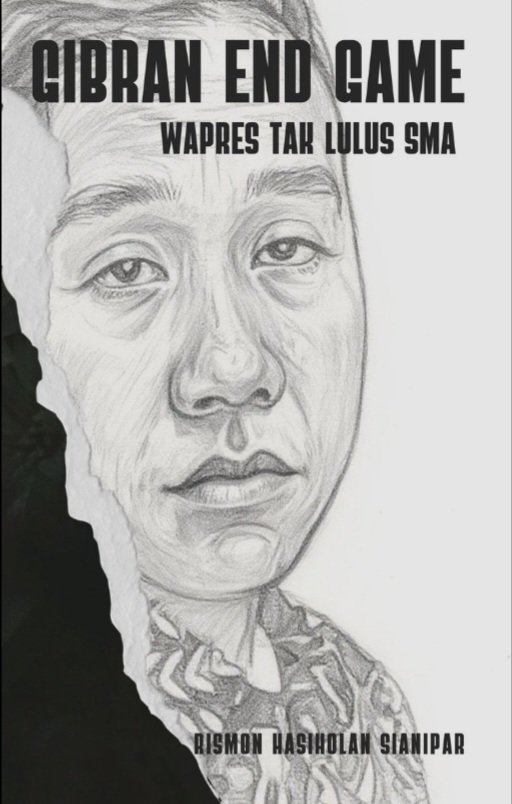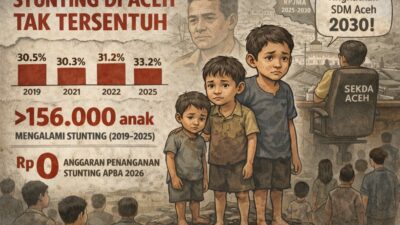Dalam demokrasi modern, karya investigatif—termasuk buku politik—sering diposisikan sebagai alat kontrol sosial. Ia memberi ruang bagi kritik, membuka tabir kekuasaan, sekaligus memperkaya diskusi publik. Namun kebebasan berekspresi bukanlah ruang tanpa pagar. Ia dibatasi oleh etika, hukum, dan tanggung jawab terhadap kebenaran.
Ketegangan inilah yang muncul ketika sebuah buku memakai judul provokatif seperti “GIBRAN END GAME: WAPRES TAK LULUS SMA”. Apakah itu bagian dari kritik politik, atau telah melampaui batas hingga menyentuh pencemaran nama baik?
Artikel ini mengurai batas-batas tersebut melalui kombinasi teori, kerangka hukum Indonesia, serta beberapa studi kasus nasional dan internasional.
Kebebasan Berekspresi dan Batas Hukumnya
Dalam kerangka demokrasi deliberatif Habermas, ruang publik dipahami sebagai arena di mana warga berdialog secara rasional, saling menguji argumen, dan mengawasi kekuasaan. Komunikasi publik, menurut Habermas, hanya dapat berfungsi bila didasari kejujuran dan itikad baik. Artinya, kritik sah bukanlah kritik yang dibangun dari asumsi atau tuduhan tak terverifikasi, tetapi kritik yang bertumpu pada argumentasi yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.
Indonesia menjamin kebebasan berekspresi melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun jaminan ini berjalan berdampingan dengan regulasi seperti KUHP dan UU ITE, yang dirancang untuk menjaga martabat pribadi serta ketertiban sosial. Dengan demikian, kebebasan berpendapat tetap berada dalam pagar hukum yang mengatur batas-batasnya.
Ketika Kritik Berubah Menjadi Pencemaran Nama Baik
Perbedaan antara kritik sah dan pencemaran nama baik umumnya terletak pada dua hal: basis fakta dan niat publikasinya. Pasal 310–311 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengategorikan pencemaran nama baik sebagai tuduhan publik yang merusak reputasi seseorang tanpa dasar yang dapat diverifikasi.
Dalam konteks buku investigatif, tuduhan seperti “tidak lulus sekolah” hanya dapat dibenarkan jika didukung bukti kuat yang dapat diuji publik. Tanpa verifikasi, tuduhan tersebut dapat dianggap sebagai serangan personal yang melanggar hukum. Kritik politik tetap diperbolehkan—bahkan diperlukan—tetapi harus dipastikan tidak berubah menjadi fitnah.
Risiko Informasi Palsu dan UU ITE
Pasal 28 Ayat (2)UU ITE Pasal 28 ayat (2) mengatur larangan penyebaran informasi palsu (hoaks) yang menimbulkan keresahan. Dalam praktik politik, informasi yang tidak diverifikasi dapat menciptakan polarisasi, mempengaruhi opini publik secara manipulatif, dan memicu eskalasi sosial. Hal ini diperkuat oleh studi yang menunjukkan bahwa dokumen palsu atau asumsi yang dipublikasikan sebagai “fakta” dapat mengacaukan stabilitas sosial dan legitimasi politik.
Dalam konteks publikasi investigatif, campuran antara fakta dan interpretasi tanpa penjelasan metodologi rawan membawa penulis ke wilayah disinformasi.
Selain kerangka hukum, ada standar etika yang mengatur produksi konten publik. Kode Etik Jurnalistik Indonesia mengharuskan verifikasi dan prinsip cover both sides untuk setiap tuduhan.
Banyak karya investigatif populer, sebagaimana dikritik De Burgh, sering terjebak pada gaya sensasional: narasi keras, tetapi metode lemah.
Karya investigatif seharusnya menggunakan metodologi riset seperti: triangulasi sumber, pemeriksaan dokumen, wawancara berimbang, dan pembuktian independen.
Tanpa standar ini, sebuah buku lebih dekat kepada propaganda ketimbang investigasi.
Pelajaran dari “Jokowi Undercover”
Kasus “Jokowi Undercover” menjadi preseden penting. Penulisnya dihukum karena mempublikasikan tuduhan tanpa bukti, seperti isu “ijazah palsu”. Pengadilan menggunakan UU ITE Pasal 28(2) karena konten tersebut dinilai sebagai penyebaran informasi palsu yang meresahkan masyarakat.
Kasus ini memberi pelajaran: menyebut suatu karya sebagai “investigatif” tidak serta-merta membuatnya bebas dari kewajiban verifikasi. Ketika tuduhan tidak memiliki bukti yang sah, karya tersebut dapat dianggap memfitnah.UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa data pribadi—termasuk informasi pendidikan—tidak boleh disebarkan tanpa izin atau dasar hukum. Tokoh politik memang berada di ruang publik, tetapi tetap memiliki hak privasi terbatas. Penggunaan dokumen pribadi dalam publikasi, apabila tanpa izin, dapat berujung pada pelanggaran privasi.
Ini penting dalam konteks buku yang mengungkap data pendidikan seseorang tanpa bukti resmi atau tanpa izin dari pemilik data.
Studi Kasus Internasional: Ketika Buku Menjadi Persoalan Pidana
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa risiko hukum bagi publikasi investigatif sangat beragam, tergantung konteks politik, jenis informasi, serta pihak yang dirugikan.
1. Julian Assange – Kebocoran Rahasia NegaraAssange menghadapi dakwaan berat di bawah Espionage Act Amerika Serikat karena membocorkan ribuan dokumen rahasia. Meskipun publikasi itu membongkar praktik militer, negara menilainya sebagai ancaman keamanan nasional.
2. Maria Ressa – Kritik terhadap Rezim DutertePendiri Rappler ini dijerat pasal cyberlibel setelah menerbitkan laporan investigatif mengenai kebijakan pemerintah Filipina. Kasusnya menunjukkan bagaimana rezim semi-otoriter dapat menggunakan hukum untuk menekan kritik sah.
3. David Irving – Penyangkalan HolocaustIrving dipenjara di Austria karena menyebarkan narasi penyangkalan Holocaust. Dalam konteks Eropa, penyangkalan genosida dianggap sebagai ujaran kebencian, bukan sekadar opini salah.
4. Gao Yu – Pembocoran Dokumen Partai Komunis TiongkokGao Yu dihukum karena membocorkan dokumen internal negara. Kasusnya menggambarkan sempitnya ruang kebebasan pers dalam negara otoriter.
5. Roberto Saviano – Ancaman dari MafiaPenulis Gomorrah tidak dipenjara, tetapi hidup di bawah ancaman pembunuhan. Ini menunjukkan bahwa risiko publikasi investigatif tidak selalu datang dari negara, tetapi juga kelompok kriminal yang merasa terancam.
Studi-studi ini mengajarkan bahwa:Kebenaran faktual saja tidak selalu cukup,niat publikasi ikut dipertimbangkan,dampak sosial publikasi dapat menjadi faktor hukum,dan risiko tidak hanya berasal dari hukum negara, tetapi juga dari aktor non-negara.
Pelajaran untuk Penulis di Indonesia
Dalam konteks Indonesia, penulis dan penerbit yang ingin menerbitkan karya bernuansa politik harus mempertimbangkan beberapa aspek:
1. Apakah tuduhan atau klaim dapat diverifikasi?Kritik sah harus berbasis fakta, bukan spekulasi.
2. Apakah ada metode riset yang jelas?Pengadilan menilai bukan hanya isi, tetapi proses memperoleh informasi.
3. Apakah data pribadi digunakan secara sah?UU PDP menuntut izin untuk publikasi data seseorang.
4. Apakah narasi dapat memicu keresahan?Jika ya, UU ITE dapat diterapkan.Tanpa mempertimbangkan semua itu, karya yang dimaksudkan untuk mencerdaskan publik justru dapat menjadi dasar tuntutan hukum.
Penutup
Kontroversi seputar buku seperti “GIBRAN END GAME: WAPRES TAK LULUS SMA” bukan hanya soal isi, tetapi juga cara memperoleh dan mengemas informasi. Kebebasan berekspresi adalah fondasi penting demokrasi, tetapi kebebasan itu harus berdiri di atas etika, metodologi riset yang kuat, dan tanggung jawab hukum.
Ruang publik, sebagaimana diidealkan Habermas, bukanlah arena untuk sensasi, tetapi ruang dialog rasional yang adil. Di era polarisasi dan klik instan, penulis dan pembaca perlu lebih kritis terhadap narasi provokatif. Kritik harus tajam, tetapi juga jujur. Fakta harus lahir dari investigasi, bukan kecurigaan.
Kebebasan berekspresi tidak menuntut kita diam, tetapi menuntut kita berhati-hati. Tanpa integritas dan verifikasi, karya politik bukan memperkuat demokrasi, melainkan menambah kebisingan publik yang menyesatkan.[]
:: Ruben Cornelius Siagian adalah seorang penulis dan analis yang fokus pada isu politik, keamanan, dan transformasi digital di Indonesia.