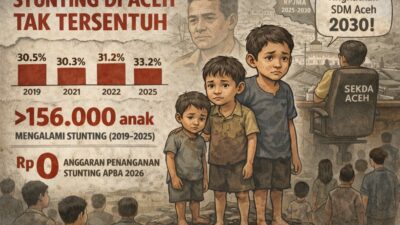FENOMENA jual beli artikel, jurnal, hingga buku akademik semakin lazim di Indonesia. Publikasi yang seharusnya lahir dari riset serius kini bisa diperoleh dengan uang, merusak etika akademik dan menurunkan marwah penelitian.
Publikasi dipandang sebagai komoditas, bukan lagi pencapaian ilmiah. Kondisi ini membuat peneliti independen, yang bekerja dengan idealisme dan keterbatasan dana, semakin tersisih karena hasil kerjanya kalah oleh publikasi instan.
Penulis, seorang peneliti independen, menuturkan bagaimana kerja keras tanpa dukungan dana maupun institusi sering diabaikan. Upayanya untuk mendapatkan pengakuan resmi, termasuk melalui BRIN dan MURI, tidak ditanggapi.
Baca juga: Jurnal SiELE USK Peringkat Satu di Asia
Situasi ini menimbulkan pertanyaan apakah penghargaan lebih mudah diberikan kepada publikasi instan yang dibeli ketimbang karya autentik. Hal ini sejalan dengan temuan Fanelli (2010) dan David (1993), bahwa tekanan publikasi mendorong praktik menyimpang serta mengutamakan kuantitas dibanding kualitas.
Studi Kasus Internasional
Masalah serupa juga terjadi di banyak negara:
Nigeria: publikasi instan menurunkan kredibilitas akademik; bahkan ada mahasiswa doktoral yang lulus hanya dengan artikel beli.
Eropa Barat: puluhan artikel ditarik setelah terungkap memakai data palsu atau jasa ghostwriting.
Baca juga: Integritas 13 Kampus Ternama tak Dipercaya, Termasuk Sebuah Universitas Negeri di Sumatra Utara
AS: banyak peneliti medis memakai jasa penulisan artikel demi karier, hingga berujung investigasi.
Tiongkok: praktik “paper mill” menyebabkan ribuan artikel internasional ditarik, mencoreng reputasi akademiknya.
India: publikasi jadi komoditas komersial, memunculkan perdebatan nasional soal etika pendidikan tinggi.
Fenomena ini menunjukkan dampak global: reputasi riset melemah, peneliti independen terpinggirkan, dan kepercayaan publik terhadap penelitian menurun.
Fenomena jual beli artikel
Praktik ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan ancaman sistemik. Publikasi hasil transaksi menciptakan “ilusi prestise” tanpa kontribusi nyata. Akibatnya, kerja keras peneliti sejati disejajarkan dengan karya instan. Temuan Plevris (2025) memperkuat bahwa tekanan publikasi mendorong plagiarisme, fabrikasi, dan jual beli artikel. Jika dibiarkan, reputasi publikasi akademik Indonesia di tingkat global akan makin rendah.
Dampak bagi ekosistem dan generasi akademik
Komodifikasi penelitian menurunkan nilai intrinsik ilmu. Norma sains menurut Mulkay (1976) dan prinsip integritas riset menurut LaFollette (1992) jelas dilanggar. Generasi muda kehilangan motivasi karena melihat jalan pintas lebih dihargai.
Hal ini berpotensi melahirkan budaya akademik permisif terhadap kecurangan. Dampaknya, universitas kehilangan fungsi sebagai penjaga integritas ilmu, sedangkan publik kehilangan kepercayaan. Nnaji (2018) menegaskan publikasi berkualitas rendah justru merusak reputasi akademik sebuah negara.
Apa yang seharusnya dilakukan Pemerintah?
Pemerintah memiliki peran kunci melalui regulasi, dukungan, dan pengawasan:
Reformasi kebijakan publikasi dengan audit etik dan transparansi.
Insentif bagi peneliti independen, agar potensi mereka tidak terbuang.
Wadah publikasi nasional yang kredibel, menekankan kualitas bukan kuantitas.
Apresiasi karya orisinal, agar peneliti muda lebih termotivasi menempuh jalur benar.
Menurut Etzkowitz & Leydesdorff (2000), kolaborasi pemerintah–universitas–industri (triple helix) penting menjaga ekosistem riset. Tanpa kebijakan adil, integritas akademik sulit pulih.
Refleksi dan Seruan Moral
Fenomena ini memunculkan pertanyaan: apakah publikasi masih bernilai jika bisa dibeli? Jika penelitian hanya komoditas, maka nilai epistemologisnya hilang.
Penelitian sejati adalah proses mencari kebenaran, bukan sekadar angka publikasi. Macrina (2014) menekankan integritas riset sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap sains.
Tanggung jawab menjaga marwah penelitian ada pada peneliti, negara, dan masyarakat. Peneliti dituntut menjaga integritas, pemerintah harus mendukung riset orisinal, dan masyarakat harus menghargai proses ilmiah, bukan sekadar hasil instan. Hanya dengan itu penelitian bisa kembali menjadi pilar ilmu pengetahuan.
Penutup
Jual beli artikel adalah ancaman serius yang merusak fondasi akademik. Prinsip utama sains—communalism, universalism, disinterestedness, organized skepticism—terabaikan. Peneliti independen dirugikan, reputasi Indonesia di dunia akademik terancam, dan generasi muda berisiko kehilangan motivasi.
Reformasi kebijakan publikasi, dukungan terhadap peneliti independen, dan apresiasi terhadap karya orisinal adalah jalan untuk memulihkan martabat penelitian Indonesia. Tanpa itu, bangsa ini hanya akan membangun rumah pengetahuan di atas fondasi rapuh.[]
:: Ruben Cornelius Siagian, seorang peneliti independen aktif menulis dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan opini publik.