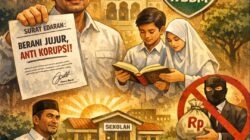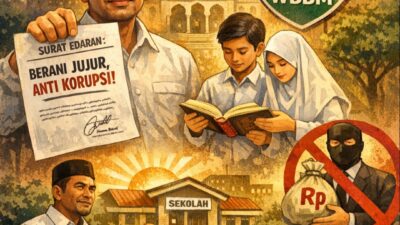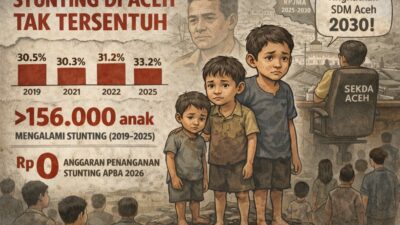PENETAPAN Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2025 memang digadang-gadang sebagai langkah monumental dalam era pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, jmdi balik narasi besar tersebut justru muncul keraguan mendasar mengenai konsistensi arah pembangunan nasional.
Pemilihan istilah “ibu kota politik” tidaklah netral. Ini menjelaskan kompromi simbolik yang berupaya menjaga legitimasi politik, tetapi sekaligus menyingkap keterbatasan pemerintah dalam mengafirmasi IKN secara penuh sebagai ibu kota negara.
Baca juga: Marak Pelacuran di IKN, MUI Plesetkan Jadi Ibu Kota Neraka
Hal ini sejalan dengan konsep symbolic politics dari Mach, Z. (1993), bahwa simbol sering digunakan untuk meredakan ketegangan sosial tanpa menyelesaikan persoalan substantif. Dalam hal ini, istilah tersebut lebih menegaskan keterdesakan politik ketimbang kesiapan hukum dan pembangunan.
Jika ditinjau dari aspek pembangunan, fokus pada gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif memperlihatkan bias pada infrastruktur kelembagaan ketimbang pembangunan sosial. Mumford, L. (2016) dalam teori urbanismenya menekankan bahwa kota bukanlah sekadar ruang fisik birokrasi, melainkan organisme sosial yang lahir dari interaksi warga, budaya, dan ekonomi.
Baca juga: Anggaran Diblokir, Proyek IKN Terhenti !
Pemindahan ASN tahap awal yang hanya 1.700–4.100 orang memperlihatkan artifisialitas IKN, yaitu sebuah kota yang berpotensi hanya hidup pada jam kerja, lalu mati ketika birokrasi selesai. Kasus Brasilia di Brasil menjadi contoh paling relevan, dimana ini dibangun dengan visi modernistis, tetapi penelitian Owensby, B. P. (1999) dan Costa, S. (2022) menunjukkan bahwa kota tersebut gagal menciptakan kehidupan sosial organik. Warga kelas bawah tersisih, sementara kota hanya menjadi etalase elite. Risiko serupa kini membayangi IKN.
Dari sisi pembiayaan, proyek bernilai ratusan triliun ini menjadi paradoks pembangunan. Dukungan pendanaan eksternal, termasuk pinjaman AIIB sebesar 1 miliar dolar AS, dapat dipandang sebagai legitimasi internasional. Namun, dalam perspektif teori dependency , seperti yang dijelaskan oleh Sylla, N. S. (2023), ketergantungan pada modal eksternal justru melemahkan kedaulatan ekonomi nasional dan memperbesar beban fiskal jangka panjang.
Studi mengenai pembangunan Naypyidaw di Myanmar memperlihatkan bagaimana relokasi ibu kota yang dibiayai besar-besaran tanpa dasar sosial yang kuat berakhir sebagai kota yang kosong dari kehidupan warga, sehingga hanya berfungsi sebagai simbol kekuasaan militer.
Tanpa mitigasi fiskal dan sosial, IKN berpotensi menjadi proyek serupa, bahwa ia mahal secara ekonomi, tetapi miskin legitimasi. Dimensi politik juga tidak kalah problematis.
Menurut teori legitimasi Weber, otoritas negara baru sah bila berlandaskan pada kerangka hukum rasional-legal. Namun, istilah “ibu kota politik” tidak memiliki pijakan konstitusional dalam UU IKN, sehingga menimbulkan potensi krisis legitimasi.
Resistensi politik pun mulai mengemuka, seperti NasDem misalnya mengusulkan agar IKN cukup menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Timur bila belum siap.
Bandingkan dengan Abuja, Nigeria, bahwa meskipun awalnya penuh kontroversi, keberhasilan Abuja ditopang oleh kerangka hukum yang jelas, insentif ekonomi, dan relokasi terstruktur. Tanpa landasan legal dan sosial yang kokoh, IKN berisiko lebih dekat pada model Naypyidaw ketimbang Abuja.
Janji Presiden Prabowo untuk mulai berkantor di IKN pada 2028 tampak lebih sebagai political staging daripada strategi realistis. Upacara kenegaraan tetap berlangsung di Jakarta, sehingga publik melihat pemindahan ini sekadar seremoni simbolik, bukan transisi substantif.
Situasi ini menempatkan Prabowo dalam dilema klasik, bahwa menghentikan pembangunan berarti melemahkan citra kontinuitas negara, sementara melanjutkannya tanpa kesiapan berarti mempertaruhkan legitimasi politik dan kepercayaan publik. Sehingga, IKN tidak lagi sekadar proyek infrastruktur, melainkan cermin dari problem struktural pembangunan Indonesia, yaitu ambisi besar yang tidak diimbangi kesiapan hukum, sosial, dan fiskal.
Studi kasus internasional memberi pelajaran bahwa Brasilia yang modern tetapi elitis, Abuja yang relatif berhasil karena legalitas dan ekosistem sosialnya, serta Naypyidaw yang mewah namun sepi. Sehingga, kita perlu bertanya, ke arah mana IKN akan bergerak?
Apakah ia menjadi ibu kota politik yang hidup dan diterima rakyat, atau justru monumen kesia-siaan, dibangun dengan utang, ditopang birokrasi rapuh, dan ditinggalkan jiwa kotanya, yakni rakyat itu sendiri?
:: Penulis, adalah seorang profesional dan akademisi. Aktif mengembangkan penelitian lintas disiplin, mulai dari astronomi dan fisika komputasi, fisika nuklir dan radiasi, fisika geologi, hingga matematika terapan dan analisis data.[]