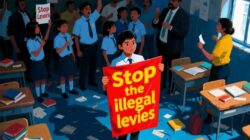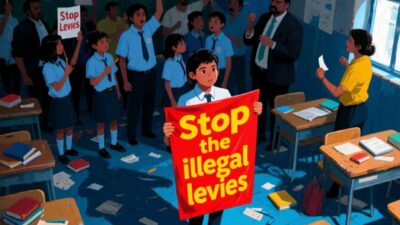KOTA ini belajar bicara dengan filter. Pemerintahnya mengaku berkolaborasi dengan influencer, bukan menyewa buzzer. Bahasa yang rapi. Tagihan yang rinci.
Pemko Banda Aceh mengalokasikan APBK 2025 untuk konten Instagram dan TikTok mencapai Rp 679 juta. Dipecah dalam tiga paket kerja, dilengkapi tarif, volume unggahan, hingga spesifikasi “makro” dan “mikro”.
Semuanya tercantum dalam rencana pengadaan dan diberitakan media arus utama. Pemerintah kota bersikukuh: ini bukan pasukan pendengung. Ini kanal informasi publik. Begitu kata juru bicara kota, Tomi Mukhtar, lengkap dengan dalih transparansi dan kebutuhan promosi daerah.
Di atas kertas, kolaborasi dengan influencer sah-sah saja. Selama akun jelas, konten bertanda, dan pesan sesuai kepentingan publik.
Baca juga: Rp 679 Juta APBK Banda Aceh Dialokasikan untuk “Buzzer”
Masalahnya, ekosistem digital kita punya kebiasaan buruk: kerja bayaran yang menyaru partisipasi warga.
Dulu, saat tagar #IndonesiaButuhKerja membanjiri lini masa, sejumlah pengampu akun mengaku dibayar untuk mengunggah dukungan ke rancangan undang-undang strategis. Publik pun mempersoalkan etika, keterbukaan, dan kemurnian opini.
Baca juga: Foya-foya Setengah Miliar Ala Disdik Aceh
Ketika narasi politik dibungkus sebagai hiburan, demokrasi diubah jadi lapak endorsement.
Riset internasional dan lokal juga menunjukkan pola berulang: tim siber berbayar memanipulasi percakapan, menyerang lawan politik, mengaburkan kritik. Oxford Internet Institute menyebut penggunaan alat “computational propaganda” oleh negara dan aktor politik untuk membentuk opini, menabur ragu, dan menciptakan kebingungan.
Di Indonesia, jejaring buzzer dipetakan sebagai operasi terorganisasi, dengan peran dari koordinator, kreator, hingga akun anonim. Industri, kata sebagian peneliti, bukan melulu komunitas. Efeknya, debat publik jadi bising, kebijakan lolos tanpa uji wajar, dan warga kelelahan memilah fakta di rimba hoax.
Contoh yang lebih telanjang: perkara “cyber army” berbayar yang diduga digerakkan untuk menyerang lembaga penegak hukum—membelokkan sorot kejahatan kerah putih dengan padatnya serangan daring. Skema rekrutmen, tarif per kepala, hingga struktur tim terungkap di pemberitaan penegakan hukum.
Ketika hukum harus berlaga dengan hoaks berseragam, kita tahu ongkos sosialnya tak kecil: kepercayaan runtuh, institusi lumpuh, dan publik makin sinis pada semua yang berlabel “informasi resmi”.
Di titik ini, Banda Aceh patut berhati-hati. Pemerintah kota sudah menolak label buzzer dan menegaskan kolaborasi dengan influencer untuk keterbukaan informasi. Baik! Tetapi, transparansi bukan sekadar menyebut angka dan paket. Ia menuntut daftar mitra, kontrak, tolok ukur keberhasilan, hingga penandaan “konten berbayar” yang konsisten.
Kalau volume unggahan dihitung ratusan kali, publik berhak tahu pesan apa yang dibeli, untuk tujuan apa, dan bagaimana pengaruhnya di ruang kebijakan. Mekanisme lapor kinerja juga wajib, bukan pilihan.
Kita butuh garis tegas antara komunikasi publik dan propaganda berbayar. Aturan pengadaan bisa mensyaratkan: larangan akun anonim, kewajiban label #iklan atau #kolaborasi, larangan penugasan yang mempromosikan narasi menyesatkan, audit independen atas metrik dampak, serta kanal pengaduan jika konten mengintimidasi kritik warga.
Platform punya tugas menertibkan, tetapi pemerintah pemesan jasa tak boleh lepas tangan. Karena, begitu uang pajak ditukar menjadi sorak digital, siapa yang memastikan kebenaran tetap di kursi pengendali?
Buzzer berjubah influencer adalah godaan untuk semua rezim—dari kota kecil hingga pusat negara. Ia tampak modern, murah, dan “engaging”. Namun demokrasi bukan soal impresi dan daya jangkau, melainkan deliberasi.
Jika pemerintah yakin sedang berdiri di sisi terang, tak ada yang perlu disembunyikan: bukalah daftar akun mitra, unggah kontrak dan deliverable, tandai konten berbayar, laporkan capaian. Barulah publik percaya bahwa kolaborasi ini benar-benar untuk warga, bukan untuk menenggelamkan mereka di kolam gema yang kian dalam: buzzer berjubah influencer.[]