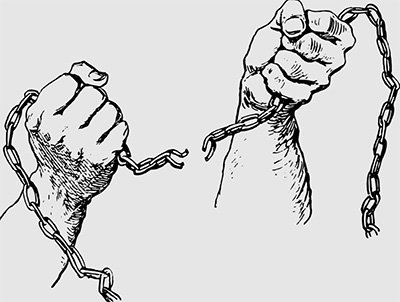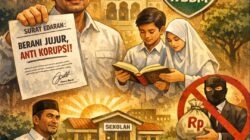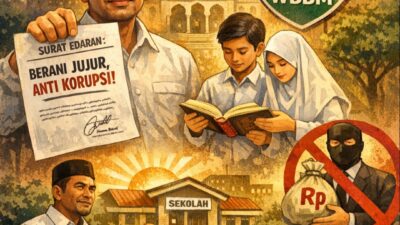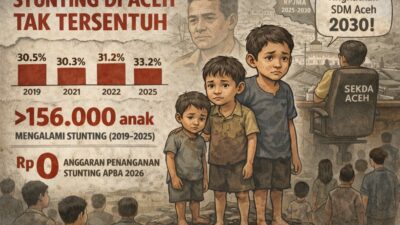SELAMAT Hari Pahlawan, 10 November. Setiap tahun, bangsa Indonesia menundukkan kepala mengenang mereka yang gugur bukan karena ambisi kekuasaan, tetapi karena keberanian moral melawan ketidakadilan.
Hari Pahlawan bukan sekadar peringatan sejarah, melainkan ajakan untuk menilai kembali makna kepahlawanan di tengah kaburnya batas antara pengabdian dan kekuasaan.
Perdebatan mengenai wacana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto menjadi cermin dari pergulatan moral tersebut. Ada yang menilai beliau sebagai Bapak Pembangunan yang membawa stabilitas dan kemajuan ekonomi, namun ada pula yang mengingat masa pemerintahannya sarat dengan pembatasan kebebasan dan ketimpangan kekuasaan.
Baca juga: Prabowo Tetapkan 10 Pahlawan, Mulai Marsinah hingga Soeharto
Pertanyaannya: apakah capaian ekonomi dapat menjadi alasan untuk menutup mata terhadap sisi-sisi gelap dalam perjalanan sejarah bangsa?
Dalam kajian etika publik dan keadilan transisional, kepahlawanan tidak hanya diukur dari hasil pembangunan, tetapi juga dari integritas moral dan keberpihakan pada kemanusiaan. Todung Mulya Lubis dalam War on Corruption: An Indonesian Experience menekankan empat prinsip utama dalam menegakkan keadilan pasca-konflik: kebenaran, akuntabilitas, reparasi, dan rekonsiliasi. Prinsip-prinsip itu belum sepenuhnya dituntaskan dalam sejarah bangsa kita. Karena itu, sebelum semua luka sosial dan sejarah terselesaikan dengan kejujuran, pengangkatan figur apa pun sebagai pahlawan perlu melalui pertimbangan etis yang matang.
Baca juga: Omong Kosong “Hari Buruh”
Selama lebih dari tiga dekade, pemerintahan Orde Baru dikenal dengan sistem kekuasaan yang menekankan stabilitas di atas partisipasi rakyat. Pemerintahan dijalankan secara sentralistis, dengan peran besar militer dalam politik dan birokrasi. Sistem seperti ini serupa dengan model bureaucratic authoritarianism yang dikenal dalam studi politik modern—menjaga ketertiban dengan membatasi ruang publik. Dalam sejarah banyak negara, pola kekuasaan semacam itu sering meninggalkan warisan sosial yang kompleks: stabilitas jangka pendek, tetapi juga kerentanan jangka panjang terhadap demokrasi dan kebebasan warga.
Salah satu aspek yang kerap menjadi sorotan dari masa tersebut adalah praktik ekonomi yang sangat terpusat pada lingkaran kekuasaan. Banyak peneliti, termasuk Todung Mulya Lubis dan sejumlah pengkaji politik kontemporer, menyoroti munculnya jaringan ekonomi yang dekat dengan kekuasaan. Jika ditinjau dari teori public virtue ethics (etika kebajikan publik), moralitas seorang pemimpin hanya sah apabila kebijakannya berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan pada kelompok terbatas. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi yang tidak disertai transparansi dan pemerataan tidak dapat disebut sebagai keberhasilan moral.
Korea Selatan dapat menjadi contoh perbandingan menarik. Negara itu berani menindak pemimpin yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan, meski mereka juga berjasa bagi pembangunan. Sikap tegas itu menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tidak boleh menghapus tanggung jawab etis seorang pemimpin terhadap hukum dan publik. Bangsa yang berani menegakkan moralitas di atas prestasi ekonomi menandakan kedewasaan politiknya.
Pola hubungan sipil-militer juga menjadi warisan besar dari masa Orde Baru. Melalui konsep Dwifungsi ABRI, militer memiliki peran ganda dalam pertahanan dan pemerintahan. Banyak kajian menyebut pola ini sebagai bentuk militerisasi kelembagaan yang mengaburkan batas antara kekuasaan sipil dan keamanan negara. Ketika militer terlalu lama berada di ruang sipil, demokrasi rentan terdistorsi, dan penegakan hukum cenderung lemah. Karena itu, pemberian gelar kepahlawanan kepada figur yang identik dengan sistem tersebut dapat menimbulkan persepsi keliru terhadap arah reformasi yang sedang dibangun.
Soeharto juga dikenal sebagai pemimpin yang piawai mengelola simbol dan narasi. Produksi karya budaya dan film sejarah menjadi alat untuk membentuk kesadaran publik tentang legitimasi kekuasaan. Sejarawan kontemporer menyebut fenomena ini sebagai rekayasa memori (engineered memory), yakni upaya merekayasa sejarah agar berpihak pada penguasa. Dalam perspektif pendidikan kebangsaan, yang perlu diwariskan kepada generasi muda bukanlah glorifikasi masa lalu, melainkan kemampuan berpikir kritis terhadap sejarah bangsanya sendiri. Pengakuan terhadap seluruh aspek sejarah—baik prestasi maupun kekeliruannya—justru menjadi dasar pembelajaran moral bagi masa depan.
Krisis ekonomi 1997–1998 menjadi titik balik dari perjalanan panjang Orde Baru. Krisis itu menyingkap rapuhnya fondasi ekonomi nasional yang bergantung pada utang luar negeri dan dominasi kelompok terbatas dalam bisnis. Dampaknya bukan hanya pada angka inflasi dan pengangguran, tetapi juga pada krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dalam etika tanggung jawab seperti yang dikemukakan Max Weber, seorang pemimpin sejati diukur bukan dari lamanya berkuasa, tetapi dari kesediaannya memikul konsekuensi moral atas tindakannya. Ketika penderitaan rakyat semakin besar dan kekuasaan tetap dipertahankan, nilai moral kepemimpinan pun dipertanyakan.
Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada figur sebesar Soeharto tentu memiliki dampak luas. Selain menimbulkan luka bagi mereka yang merasa pernah menjadi korban dari kebijakan masa lalu, keputusan itu juga berpotensi mengaburkan batas moral antara pengabdian dan kekuasaan. Generasi muda bisa tumbuh dengan persepsi keliru bahwa keberhasilan ekonomi dapat menutupi kesalahan kebijakan, atau bahwa masa kekuasaan yang panjang identik dengan kepahlawanan. Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa glorifikasi terhadap masa lalu otoriter dapat memunculkan kembali pola populisme dan nostalgia kekuasaan yang tidak sehat bagi demokrasi.
Hari Pahlawan seharusnya menjadi ajang memperkuat kesadaran moral bangsa, bukan sekadar mengenang peristiwa heroik. Kepahlawanan adalah keberanian untuk menegakkan kebenaran, menolak penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga kemanusiaan di atas kepentingan pribadi. Penghormatan kepada tokoh sejarah tentu sah, tetapi pemberian gelar kepahlawanan adalah keputusan moral dan simbolik yang memerlukan kesepakatan etis bersama. Gelar itu bukan untuk menghapus masa lalu, melainkan untuk memberi teladan moral bagi masa depan.
Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang menutupi kesalahannya, melainkan yang berani mengakui dan belajar darinya. Jujur terhadap sejarah tidak berarti menumbuhkan dendam, melainkan menegakkan martabat bangsa melalui keadilan dan kebenaran. Jika kita ingin menjadikan pembangunan sebagai warisan luhur, maka fondasinya harus kokoh di atas moralitas dan kejujuran.
Pada akhirnya, Hari Pahlawan mengingatkan kita bahwa pahlawan sejati bukanlah mereka yang memiliki kekuasaan terlama, melainkan yang berani mempertahankan prinsip kemanusiaan di tengah tekanan. Keberanian moral, bukan kekuasaan atau prestasi material, adalah inti dari kepahlawanan. Maka sebelum memberikan gelar kepada siapa pun, bangsa ini perlu memastikan bahwa keputusan itu tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga adil secara moral dan historis.
Kita patut menghargai setiap jasa pembangunan dan upaya menjaga persatuan bangsa, namun penghargaan itu tidak boleh menutup mata terhadap nilai-nilai dasar yang telah menjadi konsensus bersama: kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran. Sebab bangsa yang kehilangan orientasi moral dalam menilai kepemimpinan akan mudah terperangkap dalam siklus pengulangan sejarah yang sama.
Hari Pahlawan 10 November hendaknya menjadi pengingat bahwa kepahlawanan sejati lahir bukan dari kekuasaan, melainkan dari keberanian untuk berkata benar di saat banyak orang memilih diam. Itulah warisan yang semestinya dijaga dan diteruskan—agar masa depan bangsa tidak dibangun di atas penyangkalan terhadap sejarahnya sendiri.[]
:: Ruben Cornelius Siagian adalah seorang penulis dan analis yang fokus pada isu politik, keamanan, dan transformasi digital di Indonesia.