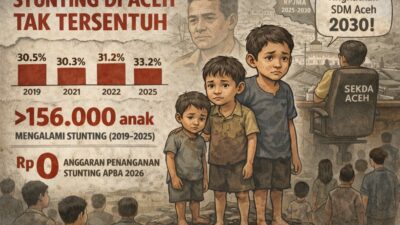Di masa lalu, kekuatan negara diukur dari jumlah pasukan dan kecanggihan senjata. Kini, yang menentukan nasib sebuah bangsa bukan lagi peluru, melainkan data dan algoritma. Ironisnya, para abdi negara yang seharusnya menjadi penjaga rahasia justru kerap menjadi celah kebocoran paling strategis.
Di balik layar aplikasi cerdas dan sistem digital yang menjanjikan efisiensi, tersembunyi pertarungan senyap antara kedaulatan nasional dan kekuasaan algoritmik global. Inilah babak baru perang tanpa dentuman senjata, perang yang menentukan siapa yang benar-benar berdaulat di era kecerdasan buatan.
Saskia Sassen (1999) menegaskan bahwa kekuasaan di era digital bergeser dari wilayah teritorial ke jaringan informasi. Negara yang tidak menguasai jaringan tersebut akan kehilangan kendali atas datanya sendiri. Ketergantungan lembaga-lembaga negara terhadap platform berbasis AI seperti ChatGPT, Google Gemini, Palantir, atau Copilot bukan sekadar urusan efisiensi, tetapi menyangkut kedaulatan epistemik—siapa yang mengendalikan pengetahuan dan memori digital bangsa.
Baca juga: Ahli IT Sebut Sosok yang Ditangkap Polisi bukan Bjorka
Fenomena ini disebut imperialisme digital oleh Garcia dkk. (2025). Negara-negara berkembang bukan hanya menjadi pengguna, tetapi juga penyumbang data mentah yang memperkuat algoritma milik negara adidaya. Informasi strategis dan kebijakan dalam negeri terserap ke dalam sistem data global yang dikuasai korporasi di AS, Israel, atau Tiongkok. Dengan demikian, kontrol terhadap data berarti kontrol terhadap kekuasaan.
Dari Meja Abdi Negara ke Server Global
Untuk memahami ancaman tersebut, bayangkan seorang analis pertahanan yang menulis laporan geopolitik dengan bantuan AI publik. Setiap kata dan data yang ia masukkan meninggalkan jejak digital yang tersimpan di luar sistem nasional. Begitu dikirim ke server AI, teks itu masuk ke tahap akuisisi data, dikumpulkan untuk pelatihan model tanpa membedakan antara data publik dan rahasia.
Kemudian, data tersebut melalui proses kurasi dan prapemrosesan, di mana algoritma membersihkan dan menyusun ulang data agar dapat dilatih ulang. Tanpa perlindungan enkripsi, laporan strategis bisa diperlakukan seperti data biasa. Kasus nyata terjadi di Korea Selatan pada 2023, ketika insinyur pertahanan tanpa sengaja membocorkan kode rahasia ke ChatGPT. Pemerintah Korea Selatan lalu melarang penggunaan AI publik untuk urusan sensitif—sebuah pelajaran bahwa setiap interaksi dengan AI berpotensi menjadi kebocoran strategis.
Baca juga: Buzzer Berjubah Influencer
Selanjutnya, data berpindah ke pusat pelatihan model yang tersebar di Amerika Serikat, Israel, dan Uni Eropa. Karena data tunduk pada hukum tempat server berada, informasi milik aparat Indonesia yang diunggah ke AI publik dapat otomatis menjadi bagian dari yurisdiksi asing. Saat pengguna berinteraksi lagi dengan sistem (misalnya meminta analisis baru), AI memanfaatkan lapisan inferensi untuk menghubungkan data lama dan baru. Walaupun perusahaan AI mengklaim data dihapus secara berkala, sebagian besar tetap tersimpan sementara untuk penyempurnaan model.
Semua data yang telah diproses akhirnya masuk ke lapisan retensi dan redistribusi, menjadi bagian dari knowledge graph—ingatan kolektif algoritma yang terus digunakan untuk melatih model berikutnya. Dalam logika machine learning, data yang telah “dipelajari” tidak bisa dilupakan, sebagaimana manusia yang tak dapat melupakan sesuatu yang sudah dibaca.
Baca juga: Kebijakan Prabowo Bagi-bagi Jabatan untuk Bekas Penculik Aktivis 98 Jadi Sorotan
Paradoksnya, semakin sering aparat negara menggunakan AI demi efisiensi, semakin banyak pula rahasia negara yang keluar dari batas kedaulatan digital. Setiap laporan yang diunggah berarti menyerahkan sebagian kontrol kepada korporasi global di luar yurisdiksi nasional. Kasus kebocoran lembaga pertahanan Eropa pada 2024 membuktikan bahwa batas antara teknologi publik dan keamanan nasional sangat rapuh.
Maka, AI bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan medan perang baru tempat kedaulatan dipertarungkan. Setiap kata yang diketik dalam sistem AI publik adalah penyerahan sebagian kedaulatan informasi kepada kekuatan algoritmik global.
AI dan Ilusi Keamanan Negara
Jean Baudrillard (1981) dalam Simulacra and Simulation menyebut modernitas menciptakan “ilusi realitas” —sesuatu yang tampak nyata namun semu. Hal ini kini terjadi di dunia intelijen. Lembaga pertahanan merasa lebih efisien dengan bantuan AI, padahal tanpa disadari mereka justru membuka pintu bagi penyusupan algoritmik yang tidak bisa dideteksi secara manual.
Penelitian Luo (2021) menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan di banyak negara berkembang belum memiliki sistem keamanan digital sekuat perusahaan teknologi global. Artinya, negara beroperasi di medan digital yang tidak mereka kuasai. Kini, lawan yang dihadapi bukan lagi agen rahasia manusia, tetapi mata-mata algoritmik—entitas nonmanusia yang mampu belajar dari perilaku pengguna tanpa mengenal batas negara dan dengan kapasitas pengawasan nyaris total.
Masalah bagi para abdi negara bukan hanya teknis, melainkan juga etis dan ideologis. Loyalitas terhadap bangsa kini diuji di ruang digital yang dikendalikan korporasi global. Michel Foucault (2012) dalam Discipline and Punish menggambarkan panoptikon sebagai sistem pengawasan permanen. Kini panoptikon itu berbalik arah: bukan negara yang mengawasi rakyat, melainkan korporasi yang mengawasi negara.
Aparat negara, akademisi, dan lembaga riset pertahanan kini bekerja di bawah pengawasan tak kasatmata perusahaan AI global. Setiap laporan dan komunikasi digital berpotensi terekam dan dipelajari. Tantangan etika muncul: bagaimana menjaga kedaulatan sambil tetap memanfaatkan teknologi?
Reorientasi Strategis
Paradoks intelijen di era AI menuntut reorientasi total terhadap cara negara memahami dan melindungi kedaulatannya. Modernisasi dan efisiensi tidak cukup; yang dibutuhkan adalah keberanian menegakkan kedaulatan data sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional. Keamanan digital harus dipandang sebagai strategi geopolitik, bukan sekadar proyek teknis.
Langkah pertama ialah mengembalikan pengolahan data strategis ke ranah offline, di lingkungan tertutup dan bebas interkoneksi global. Semua informasi yang menyangkut keamanan nasional, intelijen, dan kebijakan pertahanan harus diproses tanpa bergantung pada jaringan publik. Pemutusan sementara dari arus data global bukan kemunduran, melainkan upaya sadar melindungi inti kedaulatan dari infiltrasi algoritmik.
Langkah berikutnya adalah membangun ekosistem AI nasional berbasis infrastruktur domestik. AI tidak boleh menjadi alat kolonialisme digital yang memperkaya algoritma asing, melainkan instrumen kemandirian teknologi. Model AI lokal dengan server nasional dan pengawasan etika berlapis menjadi fondasi menuju kedaulatan digital sejati.
Namun kebijakan ini harus diiringi dengan reformulasi pendidikan pertahanan dan intelijen. Aparat negara perlu memahami cara kerja algoritma, mekanisme pengumpulan data, serta bahaya ketergantungan terhadap teknologi asing. Literasi algoritmik harus menjadi kompetensi strategis, agar disiplin menjaga rahasia negara dilengkapi dengan kesadaran epistemik tentang siapa yang mengendalikan pengetahuan digital.
Di ranah global, diplomasi digital mesti menjadi bagian dari politik luar negeri Indonesia. Negara harus memperjuangkan norma internasional tentang data sovereignty—hak setiap negara menentukan di mana datanya disimpan dan siapa yang boleh mengolahnya. Marcucci dkk. (2023) menegaskan bahwa kedaulatan digital setara pentingnya dengan kedaulatan teritorial. Dalam dunia yang diatur oleh data, kehilangan kontrol atas informasi berarti kehilangan masa depan.
Reorientasi ini pada akhirnya merupakan pilihan politik, bukan sekadar teknis: apakah bangsa ini ingin menjadi pengguna teknologi, atau pemilik pengetahuan? Dalam era AI, perbedaan antara keduanya akan menentukan apakah Indonesia tetap berdaulat, atau sekadar menjadi penyedia data bagi kekuasaan algoritmik global.
Intelijen di Persimpangan Zaman
Kita hidup di era di mana batas antara keterbukaan dan kerahasiaan semakin kabur. Intelijen kini bukan lagi soal siapa memiliki senjata paling kuat, melainkan siapa menguasai data paling dalam. Tanpa kesadaran kritis terhadap struktur algoritmik global, para abdi negara berisiko terjebak dalam sistem pengawasan yang mereka bantu bangun sendiri.
Jika negara tidak segera mengambil langkah tegas, maka paradoks itu menjadi nyata: intelijen akan menjadi nol besar di era AI, bukan karena lemahnya analisis, tetapi karena kehilangan kendali atas sumber kekuatannya, yakni pengetahuan itu sendiri.[]
:: Ruben Cornelius Siagian adalah seorang penulis dan analis yang fokus pada isu politik, keamanan, dan transformasi digital di Indonesia.