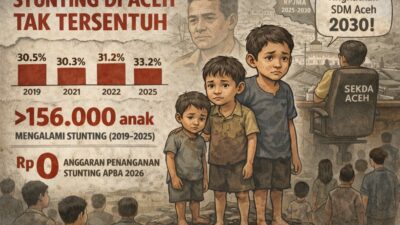ACEH kembali menjadi sorotan setelah sejumlah perusahaan asal China menyatakan minat menanamkan modal di wilayah ini. Pemerintah daerah tampak antusias menyambutnya, seolah investasi luar negeri—terutama dari Negeri Tirai Bambu—akan menjadi jalan pintas menuju kebangkitan ekonomi Aceh.
Euforia itu perlu dibingkai dengan penuh kehati-hatian. Sebab, sejarah menunjukkan bahwa investasi besar tidak selalu identik dengan manfaat besar bagi daerah penerima.
Dalam teori ekonomi klasik, ada empat faktor produksi yang menjadi penopang pertumbuhan: modal (capital), tenaga kerja (labour), sumber daya alam (resources), dan keusahawanan (entrepreneurship). Sayangnya, kebijakan ekonomi di banyak daerah, termasuk Aceh, sering kali terlalu berorientasi pada satu aspek—yakni modal atau investasi—seolah-olah uang adalah satu-satunya pendorong kemajuan.
Padahal, tanpa tenaga kerja yang kompeten, sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan, serta ekosistem wirausaha lokal yang kuat, investasi justru dapat berubah menjadi beban struktural. Aceh memiliki sumber daya alam melimpah—mulai dari tambang, perkebunan, hingga perikanan—namun kontribusi sektor-sektor ini terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat masih jauh dari optimal. Ketika investor asing datang membawa modal besar, posisi tawar lokal sering kali lemah karena tiga faktor produksi lainnya tidak diperkuat terlebih dahulu.
Baca juga: Tambang Ilegal dan Ujian Ketegasan Mualem
Minat investasi China di Aceh bukan kabar baru. Dalam dua tahun terakhir, sejumlah rencana besar telah diumumkan.
Pertama, rencana pembangunan pabrik semen di Aceh Selatan oleh konsorsium Hongshi Holding Group dan PT Kobexindo Cement dengan nilai investasi sekitar Rp 10 triliun dan kapasitas enam juta ton per tahun. Kedua, penjajakan investasi di tambang batu bara dan pembangkit listrik di Aceh Barat. Ketiga, minat investor China di sektor minyak dan gas bumi, yang telah disambut oleh Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
Angka investasi memang menggiurkan. Data Windonesia mencatat, total investasi asing langsung (FDI) di Aceh pada kuartal pertama 2025 mencapai US$ 10,3 juta, dengan sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar. Pemerintah daerah pun terlihat aktif memfasilitasi izin, menyiapkan lahan, dan mempromosikan potensi daerah ke forum-forum internasional.
Baca juga: Aceh; Tamsil Desa Subur di Pinggir Jalan Besar
Namun, yang jarang dibicarakan secara terbuka adalah bagaimana pengalaman investasi China di berbagai negara justru menyisakan persoalan serius: mulai dari ketergantungan utang, eksploitasi sumber daya tanpa transfer teknologi, hingga persoalan sosial dan lingkungan.
Belajar dari Hambantota dan Jakarta-Bandung
Kasus Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka kini menjadi contoh klasik tentang jebakan investasi (debt trap). Dibangun dengan pinjaman besar dari China, pelabuhan itu gagal menghasilkan keuntungan dan akhirnya disewakan kepada perusahaan China selama 99 tahun. Proyek yang semula dijanjikan membawa kesejahteraan, berubah menjadi simbol kehilangan kedaulatan ekonomi.
Contoh lain datang dari proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, yang juga melibatkan pembiayaan besar dari China. Setelah beroperasi, proyek tersebut menghadapi beban biaya tinggi, perpanjangan masa konstruksi, dan angka penumpang yang jauh di bawah proyeksi awal. Banyak ekonom menilai proyek ini mengandung risiko fiskal jangka panjang karena sebagian pembiayaannya dijamin oleh pemerintah Indonesia.
Baca juga: Hati-hati Mualem, Banyak Mafia di Sekeliling Anda!
Kedua contoh itu menunjukkan satu pola: investasi China kerap datang dengan pembiayaan yang kompleks, beban bunga tinggi, dan kontrak yang tidak sepenuhnya transparan. Negara atau daerah yang tidak memiliki kemampuan negosiasi kuat bisa berakhir menanggung lebih banyak risiko daripada manfaat.
Alarm di Aceh Selatan
Rencana pembangunan pabrik semen di Aceh Selatan sejatinya bisa menjadi peluang besar bagi peningkatan ekonomi lokal. Namun, rencana itu justru memunculkan tanda tanya besar.
Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa proyek tersebut tidak akan mendapat izin usaha karena masih berlaku moratorium pendirian pabrik semen baru di Indonesia. Pasalnya, kapasitas produksi semen nasional sudah mencapai 119,9 juta ton, sementara penjualan domestik hanya sekitar 65,5 juta ton per tahun. Artinya, ada kelebihan pasokan lebih dari 50 juta ton.
Bila proyek tetap dipaksakan, maka bukan saja menambah beban pasar yang sudah jenuh, tetapi juga berpotensi menghancurkan industri semen lokal yang sudah ada. Dari perspektif ekonomi regional, ini bukan investasi produktif—melainkan race to the bottom yang justru bisa menekan harga dan menurunkan kesejahteraan industri dalam negeri.
Kegagalan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan kebijakan nasional inilah yang perlu diwaspadai Aceh. Investasi besar yang tidak berbasis analisis pasar dan kebutuhan riil hanya akan menghasilkan inefisiensi ekonomi.
Pekerja asing dan isu sosial
Isu lain yang tak kalah penting adalah keberadaan tenaga kerja asing asal China di proyek-proyek investasi. Di beberapa daerah lain di Indonesia, keberadaan mereka menimbulkan gesekan sosial, terutama ketika dianggap “mengambil” lapangan kerja masyarakat lokal.
Kondisi ini berpotensi terjadi pula di Aceh, terutama di sektor pertambangan dan energi. Apalagi, banyak laporan di lapangan menyebutkan bahwa sebagian pekerja asing datang dengan kemampuan komunikasi minim dan izin kerja yang tidak sepenuhnya jelas. Tanpa regulasi tegas dan pengawasan yang kuat, hubungan industrial antara pekerja lokal dan asing bisa menimbulkan ketegangan sosial yang berkepanjangan.
Aceh memiliki rekam jejak panjang konflik antara eksploitasi sumber daya dan keberlanjutan lingkungan. Dari tambang hingga perkebunan sawit, persoalan deforestasi, sedimentasi sungai, dan pencemaran air sudah menjadi isu klasik. Jika investasi China di sektor pertambangan dan energi tidak dikelola dengan prinsip environmental governance yang kuat, maka potensi kerusakan lingkungan bisa berlipat ganda.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap proyek memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang transparan. Namun, dalam praktiknya, pelibatan masyarakat lokal sering kali hanya formalitas. Padahal, keberlanjutan sosial dan ekologis jauh lebih penting daripada percepatan izin atau janji modal besar.
Tantangan Struktural: Ketergantungan dan Kedaulatan Ekonomi
Kehadiran modal besar dari China memang bisa mempercepat pembangunan infrastruktur Aceh, tetapi tanpa desain kebijakan ekonomi jangka panjang, daerah bisa jatuh ke dalam ketergantungan baru. Ketika proyek-proyek besar dibiayai oleh pinjaman luar negeri dan dikerjakan oleh kontraktor asing, nilai tambah ekonomi yang tertinggal di Aceh menjadi minim.
Kedaulatan ekonomi daerah bukan sekadar soal siapa yang menandatangani kontrak, tetapi siapa yang menguasai rantai nilai di dalamnya: dari bahan baku, produksi, distribusi, hingga tenaga kerja dan keahlian. Jika semua dikendalikan oleh pihak luar, maka rakyat Aceh hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
Jalan Tengah: Menata ulang strategi investasi Aceh
Investasi asing tidak selalu buruk. Namun, pemerintah Aceh perlu menata ulang pendekatannya dengan menempatkan empat prinsip dasar:
1. Selektif, bukan reaktif.
Tidak semua investasi perlu diterima. Pemerintah harus memastikan bahwa proyek benar-benar sesuai kebutuhan daerah, bukan sekadar mengejar angka seremonial.
2. Berbasis kajian ekonomi dan lingkungan.
Setiap rencana investasi harus melalui market feasibility study dan AMDAL independen yang dapat diakses publik.
3. Kewajiban tenaga kerja lokal dan transfer teknologi.
Investor harus diwajibkan menggunakan tenaga kerja Aceh dan melakukan alih teknologi yang nyata, agar kapasitas lokal meningkat.
4. Keterlibatan masyarakat dan transparansi kontrak.
Masyarakat harus tahu siapa investor, bagaimana pembagian keuntungan, serta risiko yang ditanggung daerah.
Selain itu, Aceh perlu memperkuat entrepreneurship lokal agar tidak hanya menjadi penerima proyek, melainkan juga mitra sejajar dalam rantai ekonomi. Pemerintah daerah dapat mendorong inkubator bisnis, pelatihan teknis, dan pembiayaan mikro agar tumbuh kelas menengah produktif yang mampu mengambil bagian dari arus investasi.
Jangan terjebak euforia
Investasi besar kerap datang bersama pencitraan politik. Peresmian proyek, penandatanganan MoU, atau kunjungan ke luar negeri sering kali dijadikan simbol keberhasilan pemimpin daerah. Namun, investasi sejati bukan tentang jumlah uang yang diumumkan, melainkan nilai ekonomi yang bertahan di masyarakat.
Aceh pernah mengalami berbagai “proyek besar” yang akhirnya tak berkelanjutan karena minim kajian dan pengawasan. Karena itu, kehati-hatian terhadap investasi China bukan bentuk xenofobia ekonomi, melainkan sikap realistis dalam menjaga masa depan ekonomi Aceh.
Jika pemerintah daerah terlalu tergesa menandatangani perjanjian dengan iming-iming modal besar tanpa kalkulasi yang matang, maka risiko jangka panjang—kerusakan lingkungan, beban sosial, atau bahkan kehilangan kontrol ekonomi—akan jauh lebih mahal daripada manfaat jangka pendek yang diperoleh.
Arah ekonomi Aceh harus diletakkan di atas fondasi kemandirian, bukan ketergantungan. Investasi dari luar negeri, termasuk dari China, perlu disambut dengan terbuka, tetapi dengan perhitungan matang dan keberpihakan tegas kepada kepentingan rakyat Aceh.
Modal asing boleh datang, tetapi kendali ekonomi harus tetap di tangan kita sendiri. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya neraca investasi, melainkan juga masa depan generasi Aceh—apakah akan menjadi tuan di rumah sendiri, atau sekadar penonton di panggung pembangunan yang digerakkan oleh pihak luar.[]
Dr. Taufik Abd. Rahim adalah pengamat kebijakan dan pemerintahan