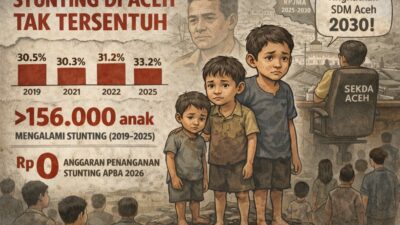GELOMBANG demonstrasi nasional pada 25–29 Agustus 2025 tercatat sebagai salah satu peristiwa politik paling besar sejak reformasi. Aksi yang bermula dari penolakan terhadap kebijakan tunjangan DPR berkembang menjadi kemarahan sosial luas yang menyorot ketimpangan ekonomi, kekerasan aparat, dan krisis kepercayaan terhadap negara.
Namun, di balik ledakan spontan itu, muncul pertanyaan yang lebih dalam: apakah gerakan tersebut benar-benar lahir dari rakyat, atau justru bagian dari rekayasa kekuasaan dan operasi intelijen politik?
Secara sosiologis, demonstrasi besar itu tidak muncul tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi dari krisis legitimasi politik, di mana publik merasa elite hidup mewah di tengah kesulitan rakyat. Isu tunjangan DPR hanyalah pemicu emosional, sedangkan bahan bakarnya adalah ketimpangan sosial-ekonomi dan rasa ketidakadilan yang menumpuk.
Teori relative deprivation menjelaskan hal ini: ketika masyarakat merasa tertinggal dari kelompok berkuasa, muncul rasa frustrasi yang mudah berkembang menjadi amarah kolektif. Ketimpangan mencolok antara rakyat dan elite menjadi katalis utama gerakan ini.
Baca juga: Demokrasi di Persimpangan: Tatkala Idealisme Mati, Pragmatisme Jadi Raja
Yang menarik, mobilisasi massa terjadi di 173 kota dalam waktu kurang dari dua hari. Kecepatan ini menunjukkan adanya mekanisme komunikasi dan jaringan yang sangat efisien, baik di dunia nyata maupun digital. Dalam kajian sosiologi politik, situasi ini disebut opportunity structure—celah kelemahan institusi yang memungkinkan munculnya aksi kolektif besar.
Dalam studi intelijen, momentum semacam itu dikenal sebagai “window of agitation”, yakni saat gejolak sosial dapat diarahkan oleh aktor yang paham peta psikologi publik. Ketika saluran komunikasi terbuka lebar dan kepercayaan terhadap institusi lemah, emosi rakyat mudah dimobilisasi, bahkan dimanipulasi.
Jejak Intelijen: Fragmentasi dan Provokasi Terkontrol
Perubahan cepat dari aksi damai menjadi kerusuhan di lebih dari 20 persen kota menandai adanya pola kekacauan yang terkontrol (controlled chaos). Di sejumlah lokasi, muncul kelompok tak dikenal yang memicu bentrokan, kemudian menghilang tanpa jejak. Fenomena ini mirip dengan operasi intelijen dalam konflik berintensitas rendah, di mana kekacauan sengaja diciptakan untuk membentuk persepsi tertentu di mata publik.
Baca juga: Keserakahan dan Hedonisme; Wajah Buram Parlemen Kita
Selain itu, di ruang digital muncul narasi propaganda yang terkoordinasi: tuduhan bahwa demonstran adalah “antek asing” disebarkan bersamaan dengan kampanye media sosial yang menyudutkan pihak tertentu. Pola ini mencerminkan operasi psikologis digital (psy-ops), yakni penggunaan informasi untuk mengacaukan opini publik dan memecah solidaritas sosial.
Tujuan utamanya bukan semata menciptakan peristiwa, tetapi mengontrol makna sosial—menentukan siapa yang tampak heroik dan siapa yang tampak bersalah. Dengan demikian, medan pertempuran tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga di ruang persepsi publik.
Motif Strategis: Uji Keamanan dan Pergeseran Isu Politik
Jika dilihat dari perspektif intelijen politik, operasi semacam ini memiliki beberapa tujuan strategis.
Pertama, mendelegitimasi lembaga publik, terutama DPR dan kepolisian, dengan cara menekan citra keduanya di hadapan rakyat. Ketika lembaga utama negara kehilangan legitimasi, aktor politik tertentu dapat masuk mengambil keuntungan.
Baca juga: Isi 17+8 Tuntutan Rakyat
Kedua, aksi ini mungkin menjadi uji coba keamanan nasional, semacam stress test terhadap sistem keamanan sosial. Dengan kerusuhan terjadi di banyak daerah sekaligus, aparat diuji dalam hal koordinasi, respons, dan loyalitas. Perbedaan cara penanganan di tiap kota—ada yang represif, ada yang permisif—menunjukkan lapisan kendali ganda, indikasi adanya pengawasan dan penilaian internal terhadap reaksi aparat.
Ketiga, demonstrasi besar bisa berfungsi sebagai pengalih isu (issue displacement) terhadap agenda politik lain yang sedang dipertaruhkan. Dalam teori agenda setting, pembingkaian isu besar di ruang publik dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menunda isu strategis lain yang lebih sensitif.
Semua tanda ini memperlihatkan bahwa demonstrasi Agustus 2025 bukan hanya luapan spontan, melainkan juga laboratorium kekuasaan untuk mengukur sejauh mana rakyat, media, dan aparat bisa dikendalikan dalam situasi krisis.
Perang Persepsi dan Manipulasi Opini Publik
Pasca demonstrasi, ruang publik dibanjiri oleh dua narasi yang saling bertolak belakang. Pemerintah menuding adanya provokasi eksternal yang memanfaatkan situasi, sementara kelompok sipil menuduh aparat menjadi pelaku kekerasan.
Pertarungan narasi ini adalah bentuk dari perang persepsi (perception management), di mana perhatian publik sengaja dialihkan dari substansi kebijakan ke konflik wacana. Akibatnya, energi sosial rakyat terserap dalam perdebatan identitas dan saling tuduh, bukan dalam perumusan solusi.
Di media sosial, situasi semakin rumit. Algoritma echo chamber memperkuat bias kelompok: pengguna hanya melihat informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Riset Putri, Purnomo, dan Khairunissa (2024) menunjukkan bahwa fragmentasi digital semacam ini membuat ruang publik mudah dipolarisasi dan rentan terhadap rekayasa opini.
Dengan demikian, pascademonstrasi menjadi ajang baru perang psikologis, bukan untuk memperjuangkan kebenaran, tetapi untuk mengatur persepsi siapa yang benar, siapa yang patut disalahkan, dan siapa yang harus diselamatkan.
Gerakan Otentik yang Disusupi Rekayasa Kekuasaan
Meski begitu, tidak semua yang terjadi bisa disederhanakan sebagai rekayasa. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak peserta aksi adalah warga biasa yang benar-benar terdorong oleh keprihatinan sosial dan idealisme. Inilah yang membuat demonstrasi Agustus 2025 memiliki dua wajah:
1. Gerakan sosial otentik, berakar pada kemarahan tulus rakyat terhadap ketidakadilan dan kemewahan elite.
2. Instrumen politik tersembunyi, di mana sebagian jaringan intelijen dan kekuasaan memanfaatkan momentum tersebut untuk menjalankan agenda pengelolaan krisis.
Gabungan dua wajah ini menjadikan peristiwa Agustus 2025 lebih dari sekadar ledakan sosial—ia adalah eksperimen politik dan psikologis terhadap perilaku massa, di mana batas antara ekspresi rakyat dan strategi kekuasaan menjadi kabur.
Fenomena ini juga menandai pergeseran besar dalam fungsi intelijen modern. Lembaga intelijen tidak lagi sebatas mengumpulkan data atau memantau ancaman, tetapi telah berubah menjadi aktor aktif dalam pembentukan opini dan pengelolaan emosi sosial.
Melalui propaganda digital, pengendalian narasi, dan operasi siber, intelijen kini mampu memanipulasi persepsi publik secara halus—tanpa perlu represi terbuka. Bentuk kekuasaan ini lebih berbahaya karena tidak kasat mata; rakyat merasa bebas, padahal emosinya diarahkan.
Tanpa mekanisme akuntabilitas dan kontrol sipil yang kuat, praktik semacam ini dapat menekan kebebasan sipil dan mengubah demokrasi menjadi demokrasi terkendali, di mana opini publik dikelola lewat algoritma, bukan dialog.
Demokrasi dalam Bayang-bayang Manipulasi
Kasus demonstrasi Agustus 2025 menjadi cermin rapuhnya demokrasi digital di Indonesia. Di satu sisi, rakyat menunjukkan daya mobilisasi luar biasa. Namun di sisi lain, kekuatan teknologi informasi membuat opini mereka bisa diarahkan oleh kekuatan tersembunyi yang lebih memahami cara kerja psikologi massa.
Kita hidup dalam ekosistem politik baru, di mana batas antara gerakan rakyat dan rekayasa kekuasaan semakin tipis. Dalam lanskap yang penuh disinformasi, publik berisiko menjadi pion dalam strategi pengendalian persepsi.
Demokrasi yang idealnya menjamin partisipasi rakyat justru menghadapi paradoks: atas nama rakyat, rakyat bisa dimanipulasi.
Pertanyaan paling mendesak dari peristiwa ini bukan lagi “siapa dalangnya”, tetapi sejauh mana sistem demokrasi mampu bertahan dari manipulasi yang dilakukan atas namanya sendiri.
Ketika aksi sosial bisa direkayasa dan emosi publik dikelola seperti variabel eksperimental, maka yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas politik, tetapi juga integritas kebebasan berpendapat itu sendiri.
Untuk itu, perlu dikembangkan kecerdasan sosial dan literasi politik digital yang kuat. Rakyat harus mampu membedakan antara gerakan otentik dan mobilisasi artifisial. Tanpa kesadaran itu, demokrasi mudah digerakkan oleh tangan-tangan tak terlihat yang bekerja di balik layar kekuasaan.
Kesimpulan
Demonstrasi Agustus 2025 menunjukkan dua hal sekaligus: potensi luar biasa rakyat dalam menuntut keadilan, dan kerentanan sistem politik terhadap manipulasi terstruktur.
Kemarahan sosial yang tulus dapat berubah menjadi instrumen kekuasaan jika saluran komunikasi publik dikendalikan oleh jaringan yang memiliki agenda tersembunyi. Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia tengah diuji—bukan hanya pada kemampuan menampung aspirasi rakyat, tetapi juga pada daya tahan terhadap operasi manipulasi yang semakin canggih.
Refleksi sederhana tapi penting: Rakyat berhak marah, tapi juga wajib waspada. Karena dalam politik modern, emosi bisa menjadi alat kekuasaan paling efektif.[]
:: Ruben Cornelius Siagian, penulis dan peneliti.